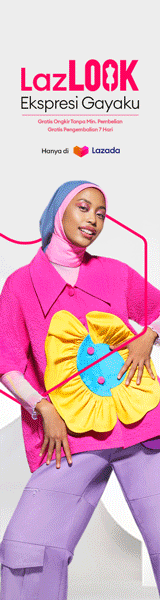Kutai Barat, Kalimantan Timur Tribunone.com: Di balik rimbunnya hutan dan kekayaan sumber daya alam Kutai Barat, tersembunyi kisah kelam tentang eksploitasi ganda yang menyandera ruang hidup masyarakat adat. Di satu sisi berdiri tambang-tambang resmi yang beroperasi atas dasar izin negara, sementara di sisi lain menjamur praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai jalan pintas masyarakat yang kehilangan akses ekonomi. Keduanya menggerus tanah, air, dan harapan warga lokal.
Warisan Izin Era Bupati Ismail Thomas: Tambang dan Sawit Rampas Wilayah Adat
Antara tahun 2006 hingga 2015, Bupati Kutai Barat saat itu, Ismail Thomas, mengeluarkan 243 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 7 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dengan total luasan sekitar 350.000 hektare. Di sektor perkebunan, 38 perusahaan sawit juga menerima konsesi seluas 202.585 hektare. Sebagian besar izin tersebut tumpang tindih dengan wilayah adat masyarakat Dayak Benuaq dan Tunjung, serta kawasan hutan lindung.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya soal luas wilayah, izin-izin itu kini menjadi polemik hukum. Ismail Thomas, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan pemalsuan dokumen izin tambang PT Sendawar Jaya. Kejaksaan menyebut ada indikasi kuat bahwa izin tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan korporasi tertentu. Kasus ini menjadi simbol dari gagalnya tata kelola sumber daya alam di Kutai Barat.
PETI: Jalan Terjal di Tengah Ketidakpastian
Ketika ruang hidup telah dibagi-bagikan kepada korporasi besar, masyarakat lokal yang kehilangan akses ke hutan dan sungai memilih bertahan lewat Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Aktivitas ini menjadi paradoks: satu-satunya sumber penghidupan yang tersisa, sekaligus memperparah kerusakan lingkungan.
PETI umumnya menggunakan merkuri, bahan beracun yang mencemari sungai dan tanah. Selain itu, para penambang rakyat ini hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi dan razia aparat. Pendapatan dari PETI pun kerap tidak sebanding dengan risiko kesehatan dan keamanan yang mereka tanggung.Dampak Sosial-Ekologis: Terjepit Antara Konsesi dan Kriminalisasi
Ruang Hidup yang Menyempit
Bagi masyarakat adat Dayak Benuaq dan Tunjung, hutan bukan sekadar sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas dan spiritualitas. Ketika konsesi menyapu bersih ladang, hutan rotan, dan sempadan sungai, maka musnah pula cara hidup turun-temurun. Di banyak kampung, konflik antara masyarakat dengan perusahaan serta ketegangan dengan aparat menjadi kenyataan harian.

Korupsi, Ketidakadilan, dan Krisis Kepercayaan
Kasus dugaan pemalsuan izin oleh Ismail Thomas membuka tabir lebih besar: penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi dalam perizinan. Publik menyaksikan bahwa sumber daya alam bukan dikelola untuk kepentingan rakyat, tetapi menjadi alat akumulasi kekayaan elite politik dan korporasi. Ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintahan pun semakin dalam.
Jalan Keluar: Enam Langkah Reformasi yang Mendesak
- Audit Menyeluruh Izin Konsesi
Seluruh IUP dan PKP2B yang dikeluarkan sejak 2006 harus dievaluasi secara hukum dan ekologis. - Cabut Izin Bermasalah
Hentikan izin yang berada di kawasan hutan lindung atau wilayah adat, terutama yang terindikasi lahir dari praktik korupsi. - Pengakuan Wilayah Adat
Legalkan dan lindungi tanah adat Dayak Benuaq dan Tunjung melalui peraturan daerah dan nasional yang konkret. - Alternatif Ekonomi Berbasis Lokal
Dorong program ekonomi berkelanjutan seperti agroforestri, ekowisata, dan kerajinan lokal sebagai pengganti PETI. - Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan
Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak ekologis PETI dan pentingnya konservasi. - Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Tindak tegas semua pelaku perusakan lingkungan, tanpa memihak antara tambang resmi dan ilegal. - Menatap Akar Masalah, Bukan Sekadar Gejalanya
PETI bukanlah masalah utama, melainkan gejala dari ketidakadilan struktural. Menyalahkan masyarakat yang menggali emas dengan alat seadanya tanpa menyentuh korporasi besar yang menguasai ratusan ribu hektare adalah bentuk hipokrisi negara. Tanpa reformasi tata kelola sumber daya alam, Kutai Barat akan terus menjadi ladang konflik dan kehancuran ekologis. (*)